
Oleh Hamid Basyaib
JIKA cita-cita bangsa Palestina terwujud untuk memiliki negara sendiri, maka negeri itu akan dengan cepat menjadi pusat keuangan di Timur Tengah. “Para pebisnis dan ahli-ahli finansial Palestina yang selama ini sukses di Amerika dan Eropa,” kata Faisal Basri, “akan berbondong pulang ke tanah Palestina dan menggerakkan perekonomian di sana, terutama sektor finansial.”
Ia mengatakan hal itu pada diskusi dalam rangkaian acara “Pekan Palestina” di kampus UII Yogyakarta, 1989. Sebagai moderator, saya terperangah mendengar uraiannya yang disampaikan dengan kalem dan sarat data. Saya merasa selama ini cukup mengikuti isu konflik Timur Tengah, tapi rupanya saya hanya berfokus pada aspek politik dan militer, dan tidak pernah memikirkan sisi yang diungkap Faisal dengan sangat baik.
Harapannya tak pernah terwujud. Palestina malah semakin robek. Status financial hub itu diraih UEA, khususnya Dubai. Rupanya ia terlalu optimistik — mungkin juga optimisme ini muncul karena dorongan simpati yang meluap pada nestapa bangsa Palestina.
Tetapi setidaknya ia mengajukan suatu analisis yang masuk akal, lengkap dengan topangan data ekonomi yang meyakinkan, tentang suatu aspek yang hampir tak pernah disinggung oleh pengamat Timur Tengah mana pun, di Indonesia maupun luar negeri.
***
Sepuluhan tahun kemudian kami berjumpa lagi di Jakarta. Kali ini ditautkan oleh semangat sama: kita perlu memanfaatkan sistem politik yang dibuka oleh Reformasi dengan membentuk partai politik. Kami merasa siap menjadi peserta dalam kontestasi demokratis untuk meraih kekuasaan, seperti sejak lama dipraktikkan di negara-negara demokrasi normal.
Dan untuk itu kami juga sepakat: kita punya Amien Rais, yang kala itu sedang di puncak popularitas sebagai tokoh utama penggerak Reformasi, dengan battle cry anti-KKN yang efektif dan disambut hangat oleh publik yang terus meluas. Dalam pandangan kami, Amien Rais harus melanjutkan perjuangannya ke arah yang logis, yaitu membentuk sebuah partai politik, dan tidak cukup hanya terus bergerak di tingkat penyadaran publik.
Fase itu sudah selesai. Jika ia tidak membentuk partai, maka berkah Reformasi hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang kurang “berhak”; jika bukan termasuk oleh mereka yang menopang sistem lama dan yang selama ini ikut berusaha membendung spirit perubahan yang disuarakan Amien Rais.
Beberapa kelompok dari beragam “garis ideologi” sepakat berharap pada Amien Rais. Dalam ungkapan Nurcholish Madjid, sekaranglah saatnya Amien Rais “takes the lead.” Ia memiliki semua kredensial yang diperlukan untuk memimpin Indonesia. Ia pemimpin Muhammadiyah, akademisi dan intelektual penting, konsisten menyuarakan Reformasi.
Ia, misalnya, pada 1988 menulis makalah panjang dengan judul tegas “Suksesi adalah Suatu Keharusan” atau semacam itu; yang artinya tidak bisa lain kecuali bahwa Presiden Suharto harus mengakhiri kekuasaannya. Dan yang tak kurang penting: pekik perubahan Amien Rais itu disambut hangat oleh kelas menengah dan bawah, elemen-elemen birokrasi, faksi-faksi tentara, dan sebagainya.
Faisal Basri tergabung dalam salah satu kelompok yang ingin mengusung Amien Rais. Setelah melewati jalan berliku — keraguan Amien sendiri untuk membentuk partai baru, “perebutan” dengan partai lama yang ingin menjagokannya, sikap setengah-hatinya untuk keluar dari “kotak Islam” dan membaur dengan para tokoh dan aktifis dari beragam warna — terbentuklah Partai Amanat Nasional (bukan “Partai Amanat Bangsa” seperti rencana semula).
Rangkaian rapat persiapan menghasilkan 9 anggota formatur untuk membentuk kepengurusan perdana PAN. Meski saya tidak termasuk 9 deklarator itu, saya ikut rapat penentuan personel di sebuah kantor perusahaan di Kuningan, dan ikut mengusulkan Faisal Basri sebagai sekjen pertama mendampingi undisputed Ketua Umum Amien Rais.
Sebentar saja terbukti bahwa Faisal Basri terlalu halus untuk menjadi mahluk politik. Ia mengeluhkan banyak hal, dan dengan kritik yang bersahabat menyalahkan saya. “Anda menjebloskan saya ke dalam partai, tapi Anda sendiri tidak mau masuk,” katanya. Saya hanya meringis dan mengulangi dalih bahwa saya wartawan, sebaiknya tidak masuk dalam struktur resmi partai.
***
Tak lama kemudian ia keluar dari PAN. Saya menerima keputusan ini dengan sepenuh maklum. Ia pasti lebih produktif sebagai pengamat ekonomi yang tekun dan tajam, seperti cirinya yang semakin kita kenal. Tapi ia, karena desakan banyak sahabatnya, sempat tergoda lagi dan mencoba bertarung di pilkada Jakarta.
Pengalaman ini tampaknya semakin mengukuhkan keyakinannya bahwa politik, setidaknya bagi seorang yang mudah menangis seperti dia, memang bukan arena yang tepat untuk mengaktualkan bakat terbesarnya.
Tempat terbaik baginya adalah lapangan riset dan advokasi ekonomi. Dan di sektor ini ia menanamkan tonggak kuat di banyak lembaga penelitian — LPPM UI, Indef, ICW dll.
Ia bukan hanya menjadi suara ide ekonomi yang tajam, tapi juga sebuah suara moral tentang keadilan sosial; suatu suara moral yang terutama bukan ia landaskan pada kitab etika umum, tapi pada rasionalitas, pada pengetahuan dan pemahamannya yang kuat tentang cara terbaik bagi suatu negara dalam mengelola ekonomi nasional yang adil.
Beberapa tahun terakhir vokalnya terdengar semakin parau, dan kritik-kritiknya semakin gamblang. Ia mengungkapkan ketaksabarannya yang kian tak tertahankan. Ia meneriakkan ketidakmengertiannya dengan emosional, kenapa ekonomi nasional dikelola dengan cara-cara yang baginya sangat merugikan Indonesia secara tak masuk akal.
***
Ketika pagi ini mendengar ia wafat, yang segera tergambar dalam lanskap kenangan saya bukanlah penampilannya yang sebersahaja dulu, dengan topi golf sebagai personal statement tambahan, tapi suasana di suatu senja di sebuah vila di Puncak. Beristirahat dari rapat persiapan program PAN di Puncak untuk salat Magrib, jamaah 4-5 orang sepakat memintanya menjadi imam.
Kami semua terkejut. Ia memimpin salat dengan qiraah yang sangat baik. Vokal tenornya yang lirih dan fasih menjadi satu-satunya suara yang terdengar di senja yang sunyi senyap itu. Semua yang ikut menjadi makmumnya bisa merasakan energi kebaikan yang muncul dari keotentikan suaranya.
Siapa tahu kelak makin banyak orang yang bersedia mendengar suara itu — hingga lama setelah pengucapnya meninggalkan mereka dalam usia 65. ***

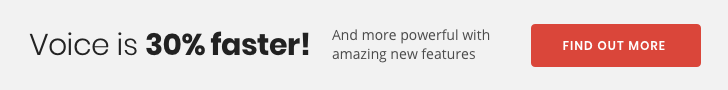





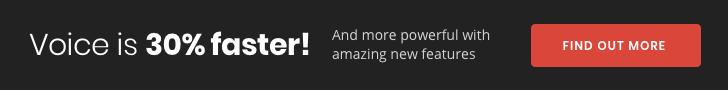
Leave a Comment